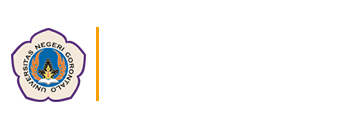Oleh: Dr. Herman Didipu, S.Pd., M.Pd.
fsb.ung.ac.id, Gorontalo – Salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran kebudayaan di perguruan tinggi adalah bagaimana agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep teoritis, tetapi juga mampu merasakan denyut hidup budaya di masyarakat. Teori memang penting sebagai fondasi, tetapi kebudayaan sejatinya bukan sesuatu yang beku di buku. Ia hidup, tumbuh, dan diwariskan melalui praktik nyata masyarakat. Karena itu, pembelajaran budaya seharusnya tidak berhenti di ruang kelas, melainkan harus menyentuh realitas kehidupan sehari-hari.
Di mata kuliah Wawasan Budaya yang saya ampu bagi mahasiswa semester awal, pendekatan tersebut coba saya terapkan. Mahasiswa tidak hanya diajak membedah konsep, teori, dan definisi tentang kebudayaan, melainkan juga diarahkan untuk turun langsung ke lapangan. Mereka diajak mengamati dan berinteraksi dengan tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat Gorontalo. Dengan cara ini, mahasiswa bisa melihat bagaimana kebudayaan bukan sekadar wacana akademik, melainkan praktik sosial yang membentuk identitas kolektif masyarakat.
Salah satu tradisi yang dipilih sebagai objek pembelajaran adalah Dikili, yakni perayaan Maulid Nabi Muhammad saw dalam tradisi Gorontalo. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya di mana nilai-nilai kebersamaan, spiritualitas, dan identitas lokal dipertemukan. Mahasiswa yang turun ke masjid-masjid sekitar dapat melihat bagaimana masyarakat menyiapkan perayaan ini, bagaimana doa dan lantunan syair dikumandangkan, hingga bagaimana makanan khas dibagikan sebagai simbol syukur.
Dalam praktiknya, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka melakukan observasi, wawancara, hingga dokumentasi terhadap perayaan Dikili yang mereka saksikan. Proses ini melatih mereka untuk peka, kritis, dan mampu merefleksikan pengalaman budaya dalam bingkai akademis. Tidak jarang mahasiswa mengaku terkesan dan baru menyadari betapa kaya dan bermaknanya tradisi lokal yang mungkin sebelumnya mereka anggap sekadar rutinitas.
Dengan model pembelajaran seperti ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami kebudayaan dari sisi konseptual, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan menghargai tradisi leluhur. Kebudayaan tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian hidup yang relevan dengan masa kini dan masa depan. Pendidikan budaya, jika dilakukan dengan pendekatan partisipatif, akan membuat generasi muda tidak tercerabut dari akar identitasnya sekaligus lebih siap menghadapi dunia global.
Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo…