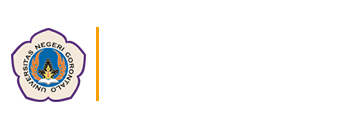Oleh Dr. Herman Didipu, S.Pd., M.Pd.
fsb.ung.ac.id, Gorontalo – Gerakan literasi di Provinsi Gorontalo sedang berada pada titik balik yang menarik. Semangat untuk membangun masyarakat membaca telah menyala, ditandai dengan tumbuhnya berbagai komunitas penggerak literasi di pelosok daerah. Namun, tantangan kita kini telah bergeser dari sekadar menyediakan buku kepada bagaimana membuat kegiatan literasi menjadi relevan, menarik, dan berkelanjutan.
Inisiatif Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pembinaan Komunitas Penggerak Literasi adalah respons yang tepat pada momentum ini. Kegiatan ini bukan lagi tentang ‘apa itu literasi’, melainkan lompatan menuju ‘bagaimana literasi dapat menjadi alat pemberdayaan’ yang menggerakkan roda sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Sebagai salah satu pemateri, saya melihat peran ini bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator yang bertugas membuka kunci potensi yang sudah ada. Setiap komunitas menyimpan energi dan kearifan lokalnya masing-masing. Tugas kami adalah membantu mereka merancang strategi, mengemas ide, dan mengelola gerakan mereka agar dampaknya lebih terasa.
Literasi harus keluar dari bayang-bayang kesan ‘elitis’ dan ‘membosankan’. Ia harus mampu menjawab persoalan sehari-hari, menjadi teman petani, nelayan, ibu rumah tangga, dan para pemuda kreatif. Literasi adalah soal menyelesaikan masalah dengan cerdas.
Kekuatan utama gerakan ini terletak pada pendekatan yang kontekstual. Sebuah komunitas di pesisir bisa mengangkat literasi kelautan dan konservasi, sementara komunitas di daerah agraris dapat fokus pada literasi tani dan pengolahan hasil bumi.
Bayangkan kekuatan yang terlepas ketika para penggerak ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga mampu menyusun proposal untuk mengadakan “Pesta Laut Baca” yang memadukan festival kuliner ikan dengan baca puisi, atau “Gerakan Literasi Tani” yang mengajak anak muda melek teknologi pertanian melalui bacaan dan pelatihan. Inilah esensi dari kapasitas manajerial yang ingin dibangun.
Tantangan terberat yang sering dihadapi komunitas adalah fase setelah pelatihan usai—saat semangat bertemu dengan realita keterbatasan dana dan sumber daya. Oleh karena itu, pembinaan ini harus dilihat sebagai langkah awal dari sebuah perjalanan panjang.
Keberlanjutan hanya akan tercipta jika terbentuk jejaring yang solid antar-komunitas dan dengan pihak pemerintah serta swasta. Kolaborasi adalah kata kunci. Komunitas tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian; mereka perlu merasa menjadi bagian dari sebuah ekosistem besar yang saling mendukung untuk kemajuan Gorontalo.
Akhir kata, partisipasi dalam pembinaan ini adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab. Ini adalah keyakinan bahwa masa depan literasi Gorontalo tidak ditentukan dari Jakarta atau pusat kota, tetapi dari desa-desa, dari ruang baca sederhana, dan dari tangan-tangan para penggerak yang tak kenal lelah.
Dengan membekali mereka dengan kemampuan manajerial dan kepercayaan diri, kita sedang menabur benih untuk masa depan Gorontalo yang tidak hanya melek huruf, tetapi juga melek peluang, kritis dalam berpikir, dan bangga akan identitas budayanya. Mari wujudkan gerakan literasi yang hidup, bernafas, dan benar-benar memberdayakan.
Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo…