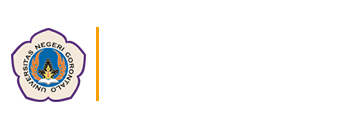fsb.ung.ac.id, Gorontalo – Istilah post-truth pertama kali muncul secara resmi dalam khazanah bahasa Internasional pada tahun 2016, ketika Oxford Dictionary memasukkannya sebagai istilah baru. Tentu saja kehadiran istilah ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia lahir dari pergulatan zaman yang ditandai oleh derasnya arus informasi sejak dunia internet membuka ruang yang begitu luas, terutama melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (sekarang berganti nama menjadi X), Youtube, Tiktok, dan masih banyak media lainnya. Di ruang itu, kita disuguhi banjir informasi yang secara substansial belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara data, rasionalitas, dan kelogisan.
Secara etimologis, post berarti melewati atau melampaui, sementara truth berarti kebenaran, maka post-truth dapat dimaknai sebagai situasi ketika kebenaran dilompati bahkan diabaikan demi opini, emosi, atau kepentingan tertentu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam ruang publik hari ini fakta objektif sering kali dikalahkan oleh narasi yang dibangun melalui bahasa yang lebih menggugah perasaan atau meneguhkan keyakinan kelompok sehingga informasi yang dikonsumsi seringkali menjadi rujukan dalam kehidupan sosial tanpa menelaah dengan baik kevalidan isi informasi tersebut. Hal ini tentu menjadi ironi, sebab apa yang diterima baik itu berita atau konten video pendek (short) jika hanya ditelan mentah tanpa mencari tahu kebenarannya atau minimal mencari informasi pembanding lalu ikut membagikan, maka dampaknya bisa sangat berbahaya. Terlebih lagi jika tujuannya adalah membodohi dan memecah belah antar sesama anak bangsa.
Tentu sudah banyak bukti tentang seberapa bahayanya menyebar informasi tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Jauh sebelumnya, Al-qur’an sudah mengingatkan di surah Al-Hujurat ayat 6 bahwa “Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita maka periksalah kebenarannya, telitilah agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu.” Di abad ini kita memang hidup pada era yang hampir mustahil membedakan yang benar dan kebohongan (bathil). Apalagi yang menyebar kebohongan menggunakan teori psikologi emotional manipulation, yaitu langsung menyasar emosi seseorang (netizen) dengan membuat judul yang bombastis, mengedit video atau gambar sampul yang tujuannya untuk menarik perhatian netizen agar mau mengklik judul meskipun isinya tidak selalu sesuai dengan isi (clikbait). Si pembuat informasi bohong akan langsung menyasar emosi netizen dan akibatnya hampir tidak ada ruang untuk berpikir kritis atau sekadar memverifikasi informasi tersebut sebelum mempercayainya. Sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, pernah berkata bahwa “Akan datang kepadamu suatu zaman ketika menerima kebathilan lebih mudah daripada menerima kebenaran”. Inilah substansi era post-truth yang digambarkan oleh Sayyidina Ali jauh sebelum istilah tersebut menjadi tren.
Fenomena ini nyata kita lihat pada berbagai isu kekinian, maraknya deepfake yang mampu memanipulasi wajah dan suara tokoh publik sehingga seolah-olah mereka mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan dengan menyalahgunakan Artificial Intelligence (AI), banjirnya informasi palsu menjelang pemilu yang disebar untuk menggerakkan sentimen emosional massa, atau clickbait berita sensasional yang ternyata hanya strategi algoritma untuk mengejar tren dan viral. Semua itu berkelindan dengan budaya share secara instan tanpa tabayyun, meminjam istilah Prof Nadirsyah Hosen “Saring sebelum sharing”. Tidak jarang pula berita hoaks sengaja dikemas dengan bahasa tertentu atau potongan data yang tampak meyakinkan, padahal jika ditelusuri lebih jauh tidak memiliki dasar metodologis sama sekali.
Di era banjir informasi ini, algoritma media sosial bekerja sangat senyap yang membuat kita hanya melihat informasi sesuai selera, kecenderungan politik, atau emosional kita. Inilah yang oleh filsuf Prancis, Jean Baudrillard menyebutnya sebagai hiperrealitas, di mana batas antara yang nyata dan yang palsu menjadi kabur. Masyarakat akhirnya hidup dalam ilusi kebenaran yang dibentuk oleh layar. Oleh karena itu, analisis wacana kritis menjadi kebutuhan, bukan hanya sekadar teori melainkan mengaktualkannya ke dalam kehidupan kita secara faktual dan tajam. Kita perlu membongkar apa yang ada di balik teks berupa konten, berita tulis, siapa yang bicara, dengan tujuan apa, serta bagaimana relasi kuasa bekerja di balik wacana tersebut. Seperti pandangan Paul Ricoeur dalam hermeneutika kecurigaannya menyarankan agar dalam menafsirkan fenomena yang ada harus selalu mengedepankan asas kecurigaan bahwa ada sesuatu di balik narasi teks, ucapan, atau pemikiran misalnya ideologi dan kepentingan.
Seperti yang ditegaskan oleh Foucault, pengetahuan tidak pernah netral. Pengetahuan selalu berkawan dengan kuasa. Artinya, berita, narasi, video pendek (short) atau bahkan meme sekalipun bisa menjadi instrumen kuasa untuk menggiring opini dan mengatur cara kita melihat realitas. Oleh karenanya, tugas kita sebagai masyarakat akademik sekaligus warga digital adalah melatih kepekaan kritis agar tidak mudah terseret arus wacana yang dibungkus rapi tetapi rapuh secara substansi.
Kita memang tidak bisa menghentikan laju derasnya arus informasi. Namun, kita masih bisa menentukan sikap apakah larut sebagai penyebar informasi tanpa kendali nalar kritis, atau hadir sebagai penyaring yang kritis dan bijak. Sikap inilah yang membedakan manusia yang berpikir dengan manusia yang hanya sekadar budak teknologi nonkritis. Mari kita jadikan tradisi kritis sebagai kebiasaan, bukan sekadar jargon. Sebab hanya dengan itu, kita bisa tetap teguh berdiri di tengah gelombang post-truth yang terus menguji kejernihan akal dan kekuatan hati. Pada akhirnya, menjaga kebenaran bukan hanya tugas intelektual, tetapi juga tugas seluruh umat manusia. (Argariawan Tamsil, M.Pd)
Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo…