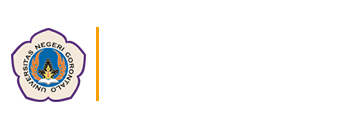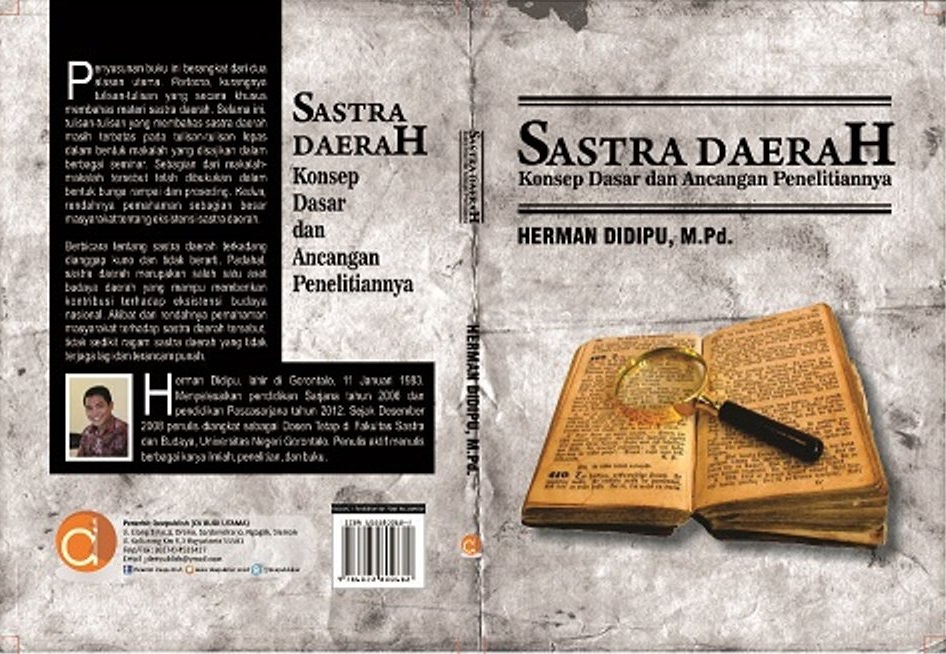Oleh: Dr. Herman Didipu, S.Pd., M.Pd.
fsb.ung.ac.id, Gorontalo – Di tengah derasnya arus globalisasi, sastra daerah ibarat harta karun yang terkubur dalam lumpur zaman – berharga, tetapi sering terabaikan. Sebagai bagian dari sastra nusantara, sastra daerah adalah kekayaan budaya yang ditulis atau dituturkan dalam bahasa lokal, seperti cerita rakyat Lahilote dari Gorontalo atau Bogani dari Bolaang Mongondow.
Meski jarang diketahui penciptanya (anonim), karya-karya ini menjadi identitas kolektif masyarakatnya. Sayangnya, modernisasi membuat generasi muda semakin asing dengan bahasa dan sastra daerah, menganggapnya kuno atau tidak relevan. Padahal, di dalamnya tersimpan mutiara kearifan lokal, petuah hidup, dan rekaman sejarah yang tak ternilai. Sastra daerah bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan cermin budaya yang memantulkan nilai-nilai luhur nenek moyang.
Ia mengajarkan etika, solidaritas, bahkan perlawanan terhadap ketidakadilan – seperti pesan moral dalam cerita Lahilote tentang kesetaraan dan kerja keras. Namun, ancaman kepunahan nyaris tak terelakkan. Minimnya minat generasi muda, pudarnya penguasaan bahasa daerah, dan kurangnya dukungan media turut mempercepat marginalisasi sastra daerah. Jika dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan karya sastra, tetapi juga akar budaya yang membentuk jati diri bangsa.
Lalu, mengapa kita harus menyelamatkan “harta karun” ini? Pertama, sastra daerah adalah fondasi kebinekaan Indonesia. Setiap cerita, mantra, atau syair lokal memperkaya mozaik kebudayaan nasional. Kedua, ia menjadi sumber inspirasi bagi sastra modern dan pendidikan karakter. Nilai-nilai dalam sastra daerah bisa menjadi penyeimbang di era digital yang serba instan. Ketiga, pelestariannya adalah bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus investasi untuk generasi mendatang. Seperti kata ahli budaya, “Sastra daerah adalah suara nenek moyang yang berbisik di tengah gemuruh globalisasi.”
Upaya penyelamatan harus dilakukan secara kolektif. Pemerintah daerah perlu menggalakkan dokumentasi dan transliterasi sastra lisan ke bentuk tulisan. Dunia pendidikan bisa memasukkan sastra daerah ke kurikulum muatan lokal, sementara media massa berperan mempopulerkannya melalui konten kreatif. Masyarakat pun bisa terlibat dengan kembali menghidupkan tradisi lisan atau mengadakan festival budaya. Contoh nyata sudah ada: beberapa daerah berhasil merevitalisasi sastra mereka melalui pentas seni dan penerbitan buku bilingual (bahasa daerah-Indonesia).
Sastra daerah bagai permata yang perlu terus digosok agar tetap berkilau. Ia bukan sekadar peninggalan, melainkan “jalan pulang” untuk memahami identitas kita yang sejati. Di tengah gempuran budaya asing, mari gali kembali harta karun ini—karena melestarikan sastra daerah berarti menjaga nyala api kebudayaan nusantara yang hampir padam. Jika bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi?
(Disarikan dari buku penulis yang berjudul Sastra Daerah: Konsep Dasar dan Ancangan Penelitiannya)
Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo…